Tari Bedhaya
Menurut Kamus Tari dan Karawitan, tari Bedhaya adalah komposisi tari klasik gaya surakarta dan Yogyakarta yang dibawakan oleh sembilan orang penari putri (Soedarsono, 1997/1978: 14). Ada beberapa jenis tari Bedhaya seperti Bedhaya Ketawang, Bedhaya Anglir Mendung, dll. Tari Bedhaya pada awal penciptaannya, ditarikan oleh putra-putri raja dan bangsawan. Setelah melaluui perkembangan zaman dan keterbukaan pihak keraton untuk melestarikan tari Bedhaya, tari tersebut bisa dipelajari oleh masyarakat luar keraton, terutama bagi mereka yang telah menjadi abdi dalem.
Tari Bedhaya merupakan tari Jawa klasik yang berasal dari keraton dan dianggap sakral. Menurut R.M. Wisnoe Wardhana, tari Bedhaya merupaakan tari yang lebih tua, lebih magis dari tari Srimpi. Kadang nama Bedhaya dikaitkan dengan akar kata "budha" sehingga dijadikan sebagai tari ritus agama asli yang berasimilasi dengan agama Budha (Wardhana. 1982: 35). Jika dianalisis lebih lanjut, tarian ini merupakan bentuk tarian batin, dalam ritus agama asli yang berasimilasi dengan agama Hindu. Hal ini juga diketahui dari beberapa pendapat. Weda Pradangga menyebutkan "...Jejer-jejer Sawi beksa sarta timbuhan gangsa lokananta (Gendhing Kemanak), binarung ing kidung Sekar Sani utawi sekar Ageng", yang berarti menari dalam posisi berbaris diiringi gamelan Lokananta, dibarengi dengan puisi metris Sekar Sawi atau Sekar Ageng (Ronggowarsito. 1884-1906: 217-218). Pada dasarnya dalam penyajian Tari Bedhaya mencakup tiga bagian yang saling melengkapi, yaitu: 1.Bagian tari yang mencakup gerak dan pola lantai dengan banyak menggunakan posisi baris.
2. Bagian karawitan yang menunjuk garap gen-dhing kemanak.
3. Bagian kidung yang menggunakan sekar kawi. Umumnya tari Bedhaya dipandang sebagai tari yang paling kuna, dan paling kompleks.
Di keraton tarian ini hanya dipagelarkan pada peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan memerlukan upacara besar seperti penobatan (jumenengan) raja baru, ulang tahun penobatan, perja-muan untuk tamu raja dan pembesar tinggi asing, serta perkawinan kerabat kerajaan (Brakel, 1991: 46).
Penari dalam tari Bedhaya biasanya berjumlah sembilan orang. Hal ini merupakan suatu simbol, para penari masing-masing membawa peran tersendiri, seperti:
1. Batak, sebagai kepala merupakan perwujudan dari jiwa.
2. Endhet-Ajeg, merupakan perwujudan nafsu atau keinginan hati.
3. Gulu, merupakan bagian leher.
4. Dhada, mewujudkan bagian dada.
5. Api-mburi, mewujudkan bagian lengan kanan.
6. Apil-Ngarep, mewujudkan lengan kiri.
7. Endhet-Wetab, merupakan perwujudan bagian tangkai kanan.
8. Apit-Meneng, merupakan perwujudan bagian tungkai kiri.
9. Buncit mewujudkan bagian organ seks (Soedarsono, 1984: 79).
Selain itu jumlah sembilan yang dipilih merupakan jumlah bilangan terbesar yang menurut pandangan kehinduan dikaitkan dengan sembilan dewa dewa penguasa makrokosmos mengitari delapan arah mata angin sebagai pusat jagat, yaitu: utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut, jumlah sembilan mengandung makna mikrokosmos dan makrokosmos. Kekuatan keduanya dipercaya bisa mensejahterahkan atau bahkan menghancurkan kehidupan. Jumlah sembilan juga merupakan gambaran jumlah semesta dan seisinya mencakup bintang, bulan, matahari, langit, bumi, air, angin, api, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Diskusi
Silahkan masuk untuk berdiskusi.Daftar Diskusi
Rekomendasi Entri
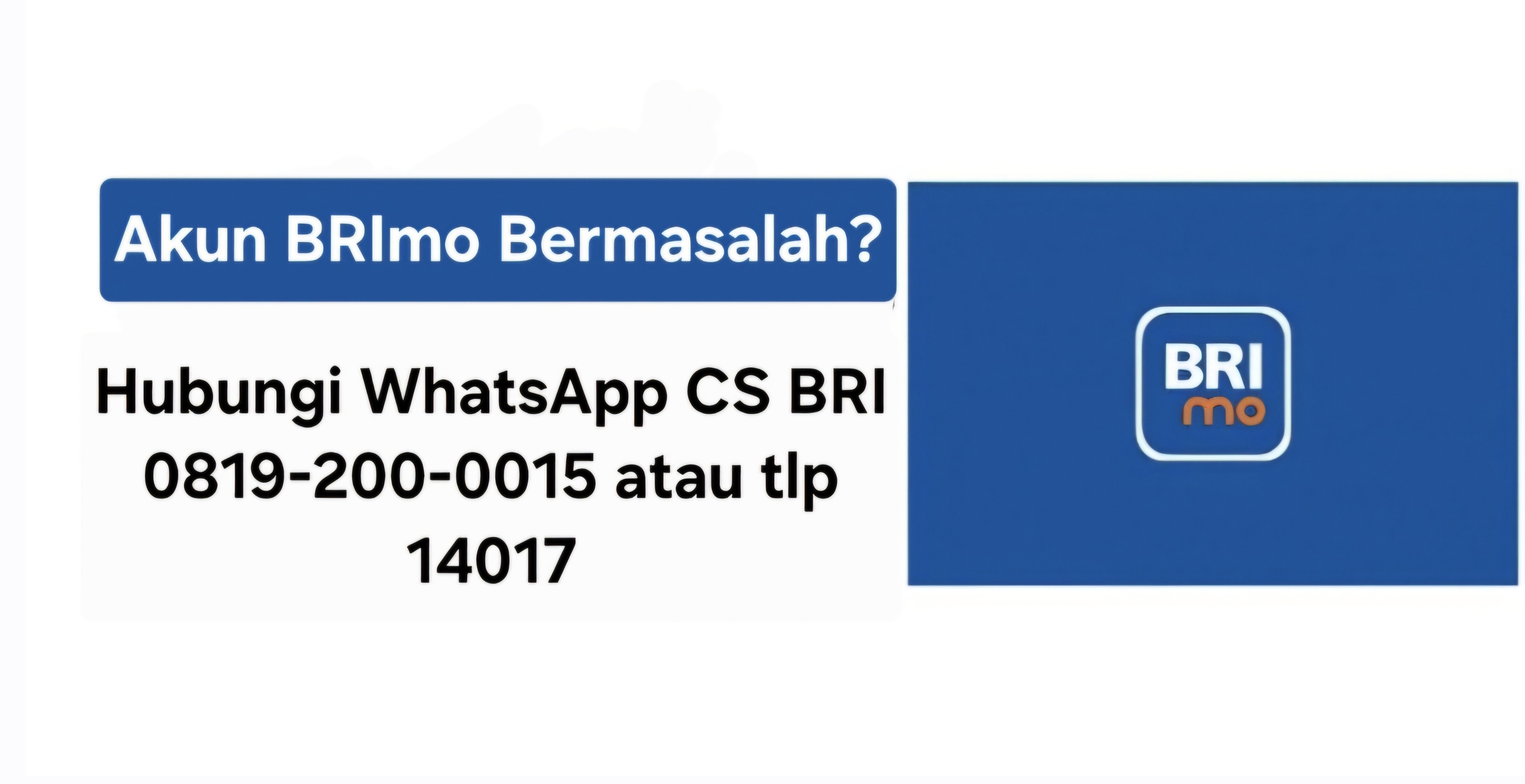
Lupa pin brimo
Untuk Mengatasi lupa PIN (BR𝖎mo) Tanpa ke bank Anda bisa menghubungi CS BR𝖎 melalui Chat WhatsApp di (628192000015) atau (1500046). Melalui aplikasi BR𝖎mo Anda bisa lupa [Username atau Password] pada halaman login Aplikasi BR𝗜mo.

BRI BRImo
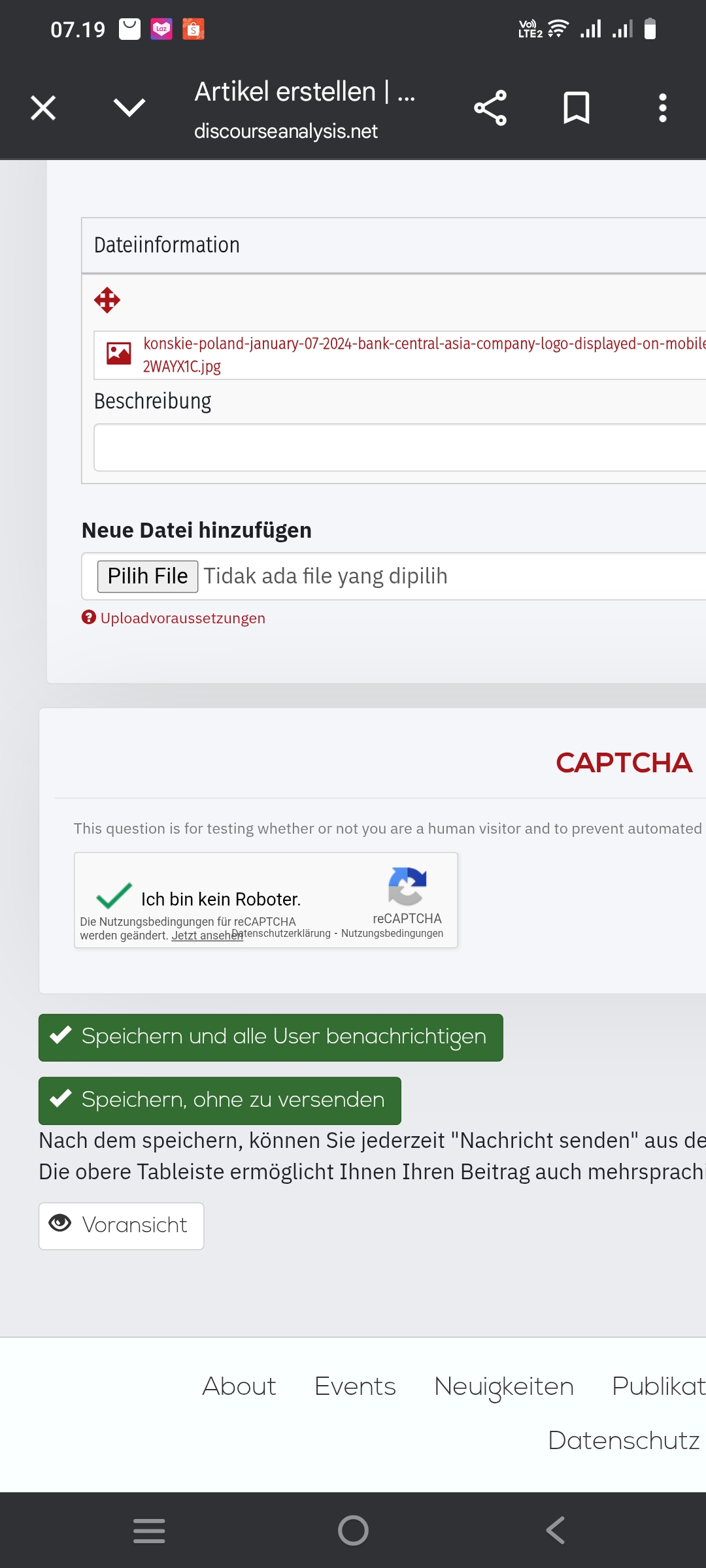
Ganti kartu ATM BNI expired bisa dimana saja?
Nasabah dapat melakukan penggantian Kartu Debit BNI melalui : 08131377201 Kantor Cabang Bank BNI terdekat dengan membawa kartu identitas (KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA/non residen)

Oskm18_16318241_athalarik Atha Larik

Apakah layanan Halo BNI 24 jam?
Ya, layanan Halo BNI melalui (+62/-0813-1377-201- WhatsApp dapat diakses 24 jam, memungkinkan Anda mendapatkan bantuan dan informasi kapan

Oskm18_16318241_athalarik Atha Larik

Cara hapus akun GoPay Pinjam?
Cara Menonaktifkan akun GO-PAY pinjam Anda hubungi pelanggan gopay~(62 0852•1165•5933) atau WhatsApp .) melalui live chat, dan siapkan data diri Anda seperti (KTP) Ikuti instruksi

Oskm18_16318241_athalarik Atha Larik

Apakah GoPay ada WhatsApp?
GoPay memiliki akun WhatsApp resmi, namun hanyhhanyhanyaaanyaa digunakan untuk keperluan promosi dan informasi marketing. Akun ininii tidak melayani keluhan atau pertanyaan pelanggan. JikaJika kamu mengalami kendala atau butuh bantuan terkait layanan GoPay, silakan hubungi kami melalui Halaman Bantuan di aplikasi GoPay-mu!

